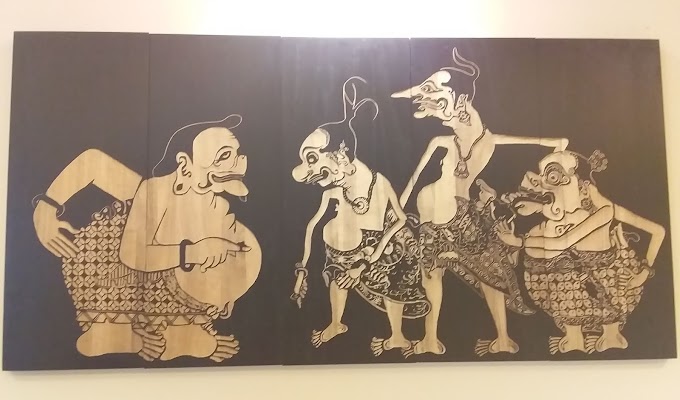Showing posts from 2018Show All
Buku Terbaru


Membaca adalah taqwa
Menulis adalah dzikir
Mengamalkannya adalah ibadah
Menyampaikannya adalah dakwah
Maka,
Ketika kata tak lagi berjiwa
Biarkanlah kisah berbicara
Ketika kisah tak mampu menyimpan jejak sejarah
Tulis semua peristiwa
Niscaya bayangan pikiran Tuhan kan terbaca
Bahwa,
Tugas kita tidak untuk pamer harta
Tidak pula untuk banyak bergaya
Melainkan untuk terus berusaha
Tugas kita tidak untuk terlihat pintar
Tidak pula untuk selalu unggul
Melainkan untuk terus belajar
Belajar mencintai apa yang kita pelajari
Belajar menekuni apa yang kita sukai
Belajar memahami apa yang tidak kita kuasai
Jadikan,
Setiap orang adalah guru
Setiap kesempatan adalah waktu belajar
Dan setiap tempat adalah ruang rindu persahabatan
Menyusun pola kebermanfaatan
Populer
Terbaru
5/recent/post-list
Kategori
- Aceh 2
- AI 1
- Akademik 1
- Al-Fitrah 1
- Al-Khidmah 1
- Atambua 1
- Balkondes 1
- Banda Aceh 1
- Banda Neira 1
- Banjarnegara 1
- Banyuwangi 1
- Batik Ciprat 1
- Belitung 2
- Belu 2
- Bengkulu 3
- Blora 1
- Bojonegoro 1
- Bondowoso 1
- Borobudur 1
- Brandes 1
- British Council 1
- Bukhari 1
- Bukit Merese 1
- Buku 7
- Cianjur 1
- Cibodas 1
- Conference 1
- Dakwah 4
- Detik 4
- Disabilitas 1
- Duta Masyarakat 9
- Essay 105
- Europe 1
- Filosofi 1
- France 1
- Frangkofoni 1
- Friendship 1
- Gamelan 1
- Garut 2
- Gastronomi 1
- Gede Pangrango 1
- German 1
- Gili Trawangan 1
- Goethe 1
- Gunung 1
- Hadiis 1
- Hadis 2
- Haul 1
- Hiking 1
- Immanuel Kant 1
- Indonesia 2
- Industri 1
- Inspiratif 1
- Instrumen 1
- Islam 4
- Jagawana 1
- Jakarta 1
- Jawa Barat 1
- Jawa Tengah 2
- Jawa Timur 1
- Jurnal 2
- Kawah Ijen 1
- Kedinding 1
- Kompas Kampus 4
- Kupang 1
- Lamongan 1
- Lingkungan 1
- Lombok 2
- LPDP 13
- Majlis 1
- Makassar 1
- Maluku 1
- Media 17
- Monash 1
- Mota'ain 1
- Negarakertagama 1
- News 46
- NLP 1
- NTB 2
- NTT 4
- NU 1
- Pamotan 1
- Pekojan 1
- Perancis 1
- Pesantren 1
- PLBN 2
- PLTSa 1
- Proceeding 4
- Puisi 4
- Ramadan 1
- Review 5
- Rote Ndao 1
- Rotterdam 1
- RPL Desa 2
- Sabang 1
- Salawat 1
- Scopus 1
- Serambi Mekkah 1
- Solo 1
- Sukoharjo 1
- Sumedang 1
- Surabaya 2
- Takjil 1
- Talaga Bodas 1
- Tawangmangu 1
- Tembang 12
- Thoughts 145
- Tiongkok 1
- Titik Nol 2
- Travel 109
- University 1
- Volunteer 6
- Wayang 1
- Wirun 1
- Wonosobo 1
- Workshop 1
- Yogyakarta 1
Copyright ©
Ardiansyah BS